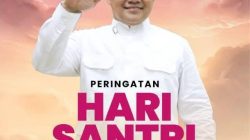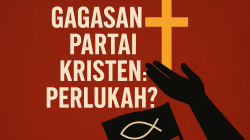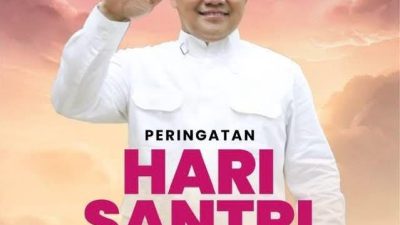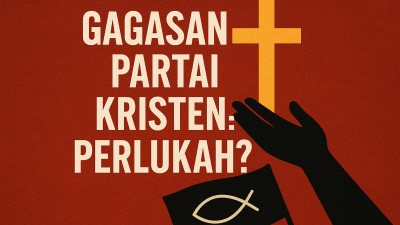Oleh: Dwi Urip Premono – Ketua SSMB (Simposium Setara Menata Bangsa)
suaralintasnusantara.com – Indonesia adalah negara majemuk yang menghadapi paradoks: kekayaan keragaman yang menjadi sumber daya sekaligus potensi konflik apabila asas kesetaraan lemah. Lebih dari 1.300 suku bangsa menunjukkan tingginya fragmentasi etnis di seluruh nusantara.
Dari sisi agama, mayoritas penduduk memeluk Islam dengan angka yang kerap dikutip mendekati 87%. Kristen (Protestan dan Katolik) sekitar 10–11%, disusul Hindu, Buddha, serta aliran kepercayaan lokal. Data administrasi dan ringkasan BPS/Kemenag mengonfirmasi komposisi ini.
Sementara di atas kertas, konstitusi kita jelas: UUD 1945 Pasal 27 menegaskan seluruh warga negara sama kedudukannya di dalam hukum, sedangkan Pancasila meneguhkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Namun, realitas sosial-politik menunjukkan jalan menuju kesetaraan masih berliku. Pluralitas etnis dan agama menjadikan Indonesia rawan gesekan karena rasa kesetaraan dan jaminan hak belum sepenuhnya nyata dirasakan seluruh kelompok.
Diskriminasi, intoleransi, dan marginalisasi masih muncul di berbagai tempat. Pertanyaannya: bagaimana agar asas kesetaraan bukan hanya slogan, melainkan benar-benar dirasakan oleh seluruh warga?
Luka yang Belum Benar-Benar Sembuh
Sejarah dua dekade terakhir memperlihatkan bahwa keretakan kesetaraan dapat berujung tragedi. Beberapa peristiwa telah tercatat, di antaranya:
1. Kekerasan terhadap kelompok minoritas agama. Contoh menonjol adalah serangkaian serangan terhadap komunitas Ahmadiyah — yang meningkat sejak fatwa MUI 2005 dan SKB 2008. Hal ini mendorong sejumlah aksi kekerasan, termasuk peristiwa berdarah di Cikeusik, Banten (2011), yang menarik perhatian media, LSM HAM, hingga pengadilan. Laporan mendokumentasikan kegagalan penegakan hukum yang memadai di sejumlah kasus.
2. Konflik komunal berskala besar. Poso (Sulawesi Tengah) menjadi contoh konflik agama-etnis yang berulang sejak akhir 1990-an. Kasus ini menunjukkan bagaimana gesekan lokal dapat berubah menjadi kekerasan berdarah apabila akar masalah—ekonomi, politik lokal, dan ketiadaan akses keadilan—tidak ditangani. Sejumlah studi akademik memetakan transisi konflik komunal menjadi kekerasan berkepanjangan di wilayah tersebut.
3. Diskriminasi berbasis ras/etnis di Papua. Laporan organisasi HAM internasional maupun lembaga negara (seperti Human Rights Watch, PBB, ASEAN) menyoroti praktik diskriminasi struktural terhadap masyarakat Papua — mulai dari akses layanan publik, kriminalisasi protes, hingga pelanggaran HAM serius yang belum tuntas penyelesaiannya. Hal ini menunjukkan bagaimana marginalisasi etnis dapat menimbulkan krisis legitimasi negara di daerah tertentu.
Ketiga catatan sejarah tersebut memperlihatkan bahwa tanpa kesetaraan, persatuan menjadi rapuh. Biaya sosial, politik, hingga nyawa yang hilang terlalu mahal untuk ditanggung.
Representasi yang Belum Setara
Kesetaraan juga dapat diukur dari representasi politik. Meski kuota 30% perempuan di parlemen sudah lama diperjuangkan, kenyataannya kursi DPR yang ditempati perempuan baru sekitar 21%. Angka itu meningkat dibanding periode sebelumnya, tetapi masih jauh dari proporsional.
Lebih sedikit lagi keterwakilan dari kelompok adat, agama minoritas, maupun penyandang disabilitas. Jika kelompok-kelompok ini tidak hadir dalam ruang pengambilan keputusan, kebijakan publik berisiko bias terhadap kepentingan mayoritas. Rendahnya representasi kelompok minoritas di legislatif dan birokrasi juga memperlemah terwujudnya kebijakan yang inklusif.
Suara Tokoh dan Moral Bangsa
Mendiang Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah berpesan bahwa pluralisme adalah bagian tak terpisahkan dari identitas Indonesia. Bagi Gus Dur, melindungi minoritas bukan hanya tugas negara, tetapi juga tanggung jawab moral bangsa.
Presiden Joko Widodo, dalam berbagai kesempatan kunjungan kenegaraan maupun kegiatan lintas agama, juga menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kehilangan semangat Bhinneka Tunggal Ika. “Perbedaan adalah rahmat, bukan ancaman,” demikian pesan yang berulang kali ia sampaikan.
Apa yang Harus Dilakukan?
Mengokohkan asas kesetaraan tidak cukup dengan jargon. Ada sejumlah langkah nyata yang perlu ditempuh:
1. Pendidikan inklusif. Sejak dini, anak-anak perlu dikenalkan pada keberagaman budaya, agama, dan etnis. Materi pluralisme, literasi media, serta pendidikan HAM harus diintegrasikan dalam kurikulum formal maupun pendidikan guru. Studi menunjukkan intervensi pendidikan dapat mengurangi sikap intoleran.
2. Peningkatan representasi politik dan kebijakan afirmatif. Dorongan agar lembaga politik lebih representatif (kuota yang efektif, pelatihan calon dari kelompok minoritas) akan membuat kebijakan nasional lebih sensitif terhadap kepentingan semua kelompok.
3. Penegakan hukum yang tegas. Aparat tidak boleh ragu melindungi kelompok yang terancam. Penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan HAM serta diawasi oleh mekanisme independen. Kasus Ahmadiyah menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas agar ada efek jera.
4. Rekonsiliasi dan pembangunan inklusif. Pengalaman Poso menunjukkan perdamaian tidak cukup dengan perjanjian damai. Diperlukan program ekonomi dan sosial yang memberi manfaat lintas komunitas, agar hubungan warga dapat kembali pulih.
5. Perlindungan hak adat dan anti-diskriminasi. Kasus Papua menuntut keseriusan negara dalam menjamin layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi setara dengan daerah lain.
6. Media dan literasi digital. Media massa dan media sosial memegang peran penting dalam membentuk opini publik. Narasi kebencian yang viral harus dilawan dengan konten positif yang meneguhkan persatuan.
Kesetaraan: Investasi untuk Masa Depan
Mengokohkan asas kesetaraan bukanlah beban, melainkan investasi kedaulatan sosial. Negara yang menjamin hak-hak semua kelompok tanpa pengecualian akan menuai stabilitas politik, pemanfaatan potensi sosial-ekonomi yang lebih luas, serta legitimasi internasional.
Ketika anak Papua mendapat akses pendidikan yang sama dengan anak Jakarta, ketika seseorang dari kelompok yang dianggap minoritas bisa memimpin negara, ketika umat beragama dapat beribadah tanpa rasa takut — di situlah Indonesia benar-benar menjadi rumah bersama.
Kesetaraan adalah fondasi kokoh bagi Bhinneka Tunggal Ika. Tanpanya, persatuan hanya retorika. Dengan kesetaraan, Indonesia bisa berdiri tegak sebagai bangsa besar yang menjadi teladan dunia.
Artikel ini ditulis untuk memberi perspektif bahwa kesetaraan bukanlah pilihan, melainkan keharusan bagi Indonesia yang majemuk.